Malam minggu 14 Mei 2016 saya datang ke acara Pesta Film Solo #6 yang mengusung tema Postalgia. Tema ini berbicara tentang film era 90-an, mengingat era tersebut film Indonesia mengalami kemacetan bahkan bisa dibilang dark age-nya film Indonesia. Acara ini diadakan oleh Kineklub Fisip UNS di Taman Budaya Jawa Tengah, Solo.
Kalau tahun lalu saya datang masih ada gandengan, tahun ini sendirian saja. Paragraf gak penting. Skip.
Saya datang di hari kedua sesi keempat, tak lain tak bukan adalah untuk menyaksikan film Bulan Tertusuk Ilalang (1995) garapan sutradara kondang, Garin Nugroho. Apalagi beliau hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang bejudul “Dirikan Fondasi, Bangkitlah Industri”. Wah, ternyata masih ada judul berima seperti ini, kupikir lagi trend-nya judul-judul lugas. Hm, baiklah langsung saja ini yang saya ingat dari diskusi waktu itu:
Setelah menyaksikan film Bulan Tertusuk Ilalang, moderator mempersilahkan para pembicara naik keatas panggung. Dimulai dari Garin Nugroho (sutradara) disusul Arturo Gunapriatna dari Lembaga Sensor Film (LSF) dan terakhir ada Adrian Jonathan dari Cinemapoetica. Diskusipun dimulai dengan agak canggung oleh moderator.
Garin Nugroho menceritakan bagaimana film Bulan Tertusuk Ilalang ini muncul ditengah chaos-nya film Indonesia pada saat itu. Jadi tahun 90-an bioskop Indonesia dipenuhi dengan film-film yang kental sekali dengan seksualitasnya. Banyak disebut sebagai film komedi seks, drama seks dan horor seks. Ditengah intervensi film seks itu, Garin kemudian membuat film yang keluar dari mainstream.
Bulan Tertusuk Ilalang dikabarkan mengalami tekanan dari pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu tidak hanya produk film, bahkan kru film pun juga tidak luput dari pantauan para intel Orba. Ancaman demi ancaman yang mengintai Garin tidak menyurutkan niatnya untuk mengerjakan film ini. Beliau berani pasang badan untuk filmnya juga untuk krunya.
Hal menarik ketika ada peserta diskusi bertanya bagaimana antusias masyarakat kala itu (era 90-an) untuk film Bulan Tertusuk Ilalang yang sangat ekspresif, mengingat disebelah saya saja ada yang ketiduran bahkan ada yang walk out. Saat pertanyaan itu dilontarkan, Garin tepok jidat. Lalu dijawab oleh Arturo Gunapriatna yang juga terlibat dalam film itu. Arturo memberi gambaran betapa getirnya selera masyarakat dan situasi politik Indonesia pada masa itu, tapi disatu sisi film tersebut justru sukses di kancah Internasional.
Campur tangan pemerintah Orba terhadap industri perfilman memang tidak main-main. Garin mengaku berulangkali berurusan dengan intel. Mulai dari surat-surat peringatan hingga kiriman misterius yang diduga bom (tapi ternyata paket souvenir). Bahkan ia sempat menunda pengerjaan film karena ketatnya pengawasan. Yang menarik bagi saya adalah kisahnya saat di Papua. Kala itu ia harus membuat film yang melibatkan orang-orang Papua dengan properti bendera Papua Merdeka. Bahkan ada scene dimana bendera Papua Merdeka dikibarkan lengkap dengan nyanyian kemerdekaan Papua. Masalah menghampiri Garin karena diluar syuting ternyata bendera-bendera dan nyanyian itu dibawa ke kota-kota oleh orang Papua sana. Tahu sendiri dampaknya apa.
Getir memang, lalu bagaimana dengan sensor film kala itu? Berbicara tentang sensor film, Arturo Gunapriatna memberikan suaranya. Arturo menyampaikan jika saat itu semua sektor memang diawasi dengan ketat, termasuk film. Sensor film lebih banyak ditekankan pada kepentingan-kepentingan yang dirasa mengancam pemerintah. Misalnya film Warkop berjudul “Kanan Kiri Oke”, pada masa itu tidak boleh “Kiri Kanan Oke”, harus diganti. Tahu sendirilah apa alasannya.
Proses pemotonganpun terbilang sadis. Jika ada scene yang dirasa berbahaya secara sepihak lembaga sensor langsung memotong scene tersebut tanpa kompromi. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Era sekarang LSF hanya memberi arahan untuk memotong scene tertentu, yang memotong film ya filmmakernya sendiri. Tapi ada juga yang bandel, Arturo bilang “kita sama-sama taulah siapa, yang filmnya main di festival luar”. Saya menduga yang dimaksud adalah Joko Anwar dengan A Copy of My Mind yang memang lugas sekali memperlihatkan lipitan pantat Tara Basro.
Arturo juga memberi gambaran, pada masa itu bioskop-bioskop Indonesia terbagi dalam tiga kelas. Berbeda dengan sekarang yang sudah meleburkan semuanya dalam hegemoni twenty-one. Saya ingat betul di seberang rumah saya dulu ada bioskop daerah bernama Studio 1.2.3. Uniknya tontonan untuk orang dewasa adalah film Indonesia dengan unsur seksualitas yang tinggi. Sedangkan sajian untuk remaja dan anak justru film-film luar seperti Small Soldier, Jurassic Park hingga Titanic.
Maka saya pikir tak heran jika pemuda sekarang banyak yang nge-judge film Indonesia sebagai film sampah. Efek traumatik tontonan film saat kami masih kecil disebabkan lebih banyak dicekoki film-film luar. Apalagi saat menginjak usia puber kami mengalami de javu dengan munculnya film-film macam Kuntilanak Kesurupan di Malam Pertama sambil Ngesot Ketetesan Darah Perawan Suster Miyabi Goyang Pinggul di Rumah Pasung apapunlah itu judulnya #sukasukamasnayatosaja #kamipasrah . Untuk masalah sensor ini patut diucapkan terimakasih untuk Yulia Hesti dari Ruang Film Semarang atas pertanyaannya yang detil, hingga memicu jawaban mantap.
Obrolan malam itu kian menarik dan Garin pecah sekali menyampaikan materi dengan punchline yang rapi. Yang sangat disayangkan adalah Adrian Jonathan. Meski saya suka tulisan-tulisan di Cinemapoetica tapi saat sesi diskusi Adrian sepertinya agak canggung. Baik dari intonasi atau tempo bicara yang terlalu saykojic banget plus penguasaan mic yang kurang baik membuat perkataannya kurang jelas terdengar. Maaf saya tidak bisa mengutip apa-apa dari bagiannya Adrian. Ngomong-ngomong saat Adrian naik panggung, mbak-mbak belakang saya ada yang nyeletuk “Ya ampun, perutnya njembling gitu”. Dengan sigap saya memperbaiki posisi duduk sambil masukin tangan ke saku jemper, barangkali bisa sedikit membiaskan.
Sebelum saya akhiri, ada sedikit tambahan nih. Garin sempat memberi motivasi dalam pengkaryaannya. Ditengah ancaman dan kecaman yang melingkarinya, beliau bandel sekali mengerjakan film. Beliau ibaratkan seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola akan menyakiti dirinya sendiri jika ia berhenti bermain bola. Ilmuwan akan menyakiti diri jika ia berhenti mencari ilmu. Sutradara pun juga demikian, Garin merasa sakit oleh dirinya sendiri jika berhenti membuat film. Daripada menyakiti diri sendiri yang sudah pasti sakit, beliau gambling saja. Beliau tetap membuat film. Kalau ada serangan dari luar ya terima itu sebagai resiko, kalau tidak ada ya syukur. Jadi buat para sineas ayo terabas saja!
Selebihnya jika ingin memahami perjalanan film Indonesia secara runtut dari masa kolonial hingga sekarang kita bisa membaca buku “Krisis dan Paradoks Film Indonesia” tulisan dari Garin Nugroho dan Dyna Herlina. Buku ini bagus sekali, ringan dibaca dan penting.
Oke, segini saja yang bisa saya tulis. Sebenarnya masih banyak yang dibicarakan pada malam diskusi itu, tapi yang saya share segini saja ya. Cuma modal ingat-ingat nih, puyeng juga pagi-pagi diajak mikir keras. Terimakasih buat kalian yang mampir di blog saya dan maaf kalau ada tersinggung. Mari kita tutup dengan quote dari Garin:
“Sutradara itu BAJINGAN! Kalau anda mau jadi orang baik-baik, mau masuk surga, jangan jadi sutradara.” (Garin Nugroho, 2016)
Source pict: antarariau.com

.png)





.jpg)

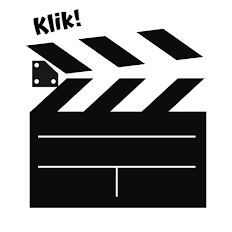

Keren mas! Dateng lagi yaa di Pesta Film Solo tahun selanjutnyaa
BalasHapusWah, paniti ya? Makasih ya sudah baca repiew acara :D
Hapus